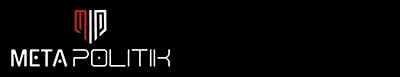Penulis: Garin Nugroho (Sutradara dan Budayawan; Pengajar Pascasarjana ISI Surakarta/Yogyakarta)
metapolitik.id – Era politik dan hiburan dalam media sosial dewasa ini disebut sebagai era kebangkitan narasi. Sebuah kebangkitan manusia yang hakikatnya disebut homo narrans, makhluk bercerita, memahami dan membentuk dunia lewat cerita. Kebangkitan era narasi ini bisa dirujuk pada dua wajah yang populer di media sosial, yakni politik narasi yang teramplifikasi di media sosial, bahkan sering disebut media sosial telah berevolusi mendasari sistem komunikasi politik Indonesia.
Di sisi lain, periode lima tahun ini adalah periode emas film dan seri drama Indonesia di bioskop maupun berbagai platform media sosial. Data menunjukkan, film Indonesia mengalami pelompatan penonton hingga 80 juta penonton, bahkan box office film Indonesia berkisar 8 juta penonton, mengalahkan pencapaian box office film Hollywood. Masa emas ini ditandai munculnya paradoks, di satu sisi lahirnya generasi muda dengan karya-karya yang berkualitas sekaligus produktif. Di sisi lain, era media baru melahirkan kompetisi dengan narasi banal merebut pasar.
Politik narasi merujuk kemampuan menceritakan sebuah kompleksitas menjadi tuturan sederhana untuk daya tarik sekaligus kepercayaan publik. Film dan drama seri lewat bangunan narasinya bertujuan mengajak warga untuk menonton, mengalami, dan menanggapi kehidupan, baik sebagai hiburan pelepas berbagai masalah, gaya hidup, kecintaan pada diva, gugatan, inspirasi, hingga pengalaman emosional untuk berelasi dengan berbagai kenyataan sekitarnya.
Simak rentetan film yang diambil dari konten kisah nyata populer dari konten media sosial tentang perselingkuhan dalam rumah. Sebutlah film Ipar adalah maut yang meraup hampir 5 juta penonton, menjadi 10 besar film terlaris Indonesia. Berkisah perselingkuhan antara adik ipar dan kakaknya, diadaptasi dari kisah nyata follower konten Tiktok yang viral. Menyusul sederet film perselingkuhan dalam rumah antara suami (Deva Mahendra) dan pembantu (Ariel Tatum) bertajuk La Tahzan.
Di sisi lain, film membawa penonton pada kepahlawanan, beragam profesi dan peristiwa, nilai hingga harapan. Simak film Habibie dan Ainun mencapai hampir 5 juta penonton. Atau belajar dari drama Korea (drakor), sangat populer karena penonton mampu mengalami banyak profesi sekaligus peristiwa yang berelasi dengan kehidupan, dari profesi atlet angkat besi, ahli hukum, astronot, hingga militer yang membawa inspirasi beragam kehidupan dan bergam jenis laku kepahlawanan sehari-hari.
Maka, sungguh menarik mengkaji wajah politik dalam film Indonesia. Secara berseloroh, kaitan film dengan politik bisa terepresentasikan lewat film horor, ketika 70 persen Indonesia didominasi film horor. Simaklah, ciri film horor serba hantu bergentayangan tidak sampai tujuan, seolah merujuk perilaku elite politik yang program-programnya sering tidak sampai pada tujuan. Atau simak sosok hantu yang tampil cantik, tetapi ketika didekati menjadi menyeramkan, bahkan berperilaku menakutkan, layaknya perilaku elite politik, awalnya terlihat baik, tetapi kemudian menjadi laku banal politik.
Demikian juga, film horor yang serba menuntut respons kaget dengan mengelola rumus jump scare. Jangan heran, kebijakan politik Indonesia juga dipenuhi keterkejutan, simak keluhan warganet atas lonjakan tarif listrik setelah diiming-iming diskon 50 persen, atau simak kebijakan-kebijakan baru tanpa sosialisasi.
Penggampangan
Politik dan film Indonesia hidup dan dihidupi dalam ekosistem beragam platform, maka segalanya diperlakukan layaknya konten. Yakni segala jenis materi yang dibagikan melalui platform media sosial untuk menarik perhatian dan keterlibatan. Jangan heran, di tengah kebisingan konten video media sosial, politik narasi maupun film berusaha dikelola layaknya konten, yakni mudah ditangkap, mengikuti tren, mengelola pengalaman emosional, unsur-unsurnya mudah diterjemahkan ke dalam berbagai platform.
Semua aspek tersebut mengabdi pada tujuan utama, yakni kepopuleran. Bisa ditebak, alih-alih mengelola konten dengan sikap kreatif, kritis, komunikatif, maka persaingan dan kebisingan beragam konten, mendorong lomba meraih pasar banal, bahkan headline atau judul harus langsung membangun respons cepat. Simak judul film horor yang aneh tapi nyata, Suster Keramas, Pocong Mandi Goyang Pinggul, Mr. Bean Kesurupan Depe. Segalanya terasa antilogika tontonan dan penggampangan. Simak, atas nama viral, maka seleksi bintang film diukur dari jumlah follower. Sementara itu, simak film atau drama seri Korea, mereka tidak terjebak segalanya berbasis formula konten, tetapi tetap pada kreativitas dengan berbagai sumber materi dalam hukum narasi film.
Pada gilirannya, di tengah harapan keterlanjutan masa emas, film Indonesia tersandera oleh jalan gampang pencapaian popularitas serta pencapaian target guna pemenangan pasar. Hal ini juga terbaca pada politik Indonesia yang berjargon Indonesia Emas 2045. Penyanderaan ini melahirkan suburnya laku politik superfisial alias kemasan yang jauh dari esensi, merebaknya jurus mengelola keterlibatan emosional tanpa sifat kritis alias logika, tetapi juga terkikisnya kerja membangun platform ekosistem yang sehat, produktif, kritis, dan berjangka panjang dalam kompetisi dunia. Simak film-film Indonesia di OTT international, 90 persen masih tayang regional. Simak indeks berkait kualitas bangsa, tergolong rendah di ASEAN, dari indeks IQ, produktivitas, literasi, hingga pendidikan.
Sesungguhnya, abad kebangkitan narasi yang berciri serba sederhana sekaligus populer adalah sebuah tantangan mulia yang memberi ruang karya berkualitas, populer, dan inspiratif. Sebuah kemuliaan yang tidak mungkin dilakukan lewat jalan pintas penggampangan. Harus digarisbawahi, jalan penggampangan akan melahirkan terkikisnya profesionalisme. Pada gilirannya, kekuatan narasi hanya mengambil unsur-unsur bersifat kemasan yang superfisial, tetapi abai pada kualitas berbagai unsur utama bangunan narasi.
Dalam perbandingan pada drakor, semisal adegan dokter di rumah sakit, maka mereka membangun set rumah sakit hingga ruang operasi sangatlah profesional seperti pada film Hospital Playlist. Demikian juga ruang artistik pada drakor berkisah pusat peluncuran misi luar angkasa di film The Moon. Sementara drama seri Indonesia atau film, ruang profesi seperti rumah sakit hanyalah latar, bahkan profesi dokter tidaklah menyentuh kerja detailnya. Harap mafhum, drama seri Indonesia terasa tidak menghidupi sungguh-sungguh beragam ruang profesi.
Kehilangan momentum
Pada gilirannya, film Indonesia kehilangan pencinta film sejati, kehilangan fondasi dasar pasarnya. Penonton terbatas mengejar isu dangkal, tren, hingga pameran gaya hidup serta fans diva. Sementara itu, penonton film Korea dan drakor merujuk kerja profesional yang terasakan di berbagai unsur film, baik bangunan karakter, profesi, setting peristiwa, hingga story telling yang membawa inspirasi.
Bahkan film dan drama seri Indonesia terasa tidak lagi punya keberanian mengangkat nilai-nilai kehidupan yang justru menjadi kekuatan narasi film Korea. Simak nilai konfusius dalam film Korea, seperti respek hingga kerja keras, menjadikan digemari ibu-ibu yang ingin menuntut kisah menarik sekaligus mendidik.
Hal ini juga terepresentasi pada wajah politik Indonesia. Politik kehilangan warga politik yang berkualitas, warga yang mampu melakukan partisipasi kontruktif dan kritis. Namun, yang muncul di medsos lebih pada dukung-mendukung banal, isu selingkuh, korupsi, perdebatan kasar, pameran kekayaan, hingga kedangkalan pernyataan elite politik serta berbagai kekerasan simbolik maupun fisik.
Pada akhirnya, sekiranya terus berlanjut, era kebangkitan narasi kehilangan momentum membangun ruang publik hiburan dan politik yang produktif, populer, tetapi inspiratif. Menjadi ironis, modal besar jumlah penduduk tidak lagi dikelola serius sebagai masyarakat sipil yang terus diperbaiki kualitasnya, mengakibatkan terkikisnya fondasi dasar industri kreatif yang sehat dan produktif, yang tidak hanya mengikuti pasar, tetapi juga memperbaiki selera dan membentuk pasar berkualitas.
Celakanya, skema kebijakan strategi membangun masyarakat sipil yang kritis dan produktif dari pemerintah belumlah terasa hadir. Harap mafhum, menonton wajah politik Indonesia layaknya menonton film dan seri drama Indonesia, riuh tapi rendah kualitasnya.
Sumber: kompas.id
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari.